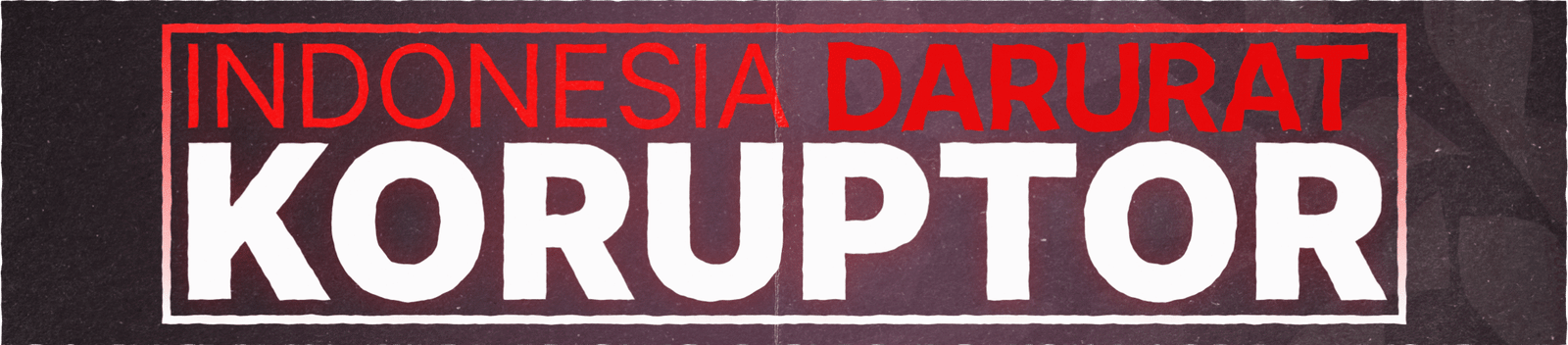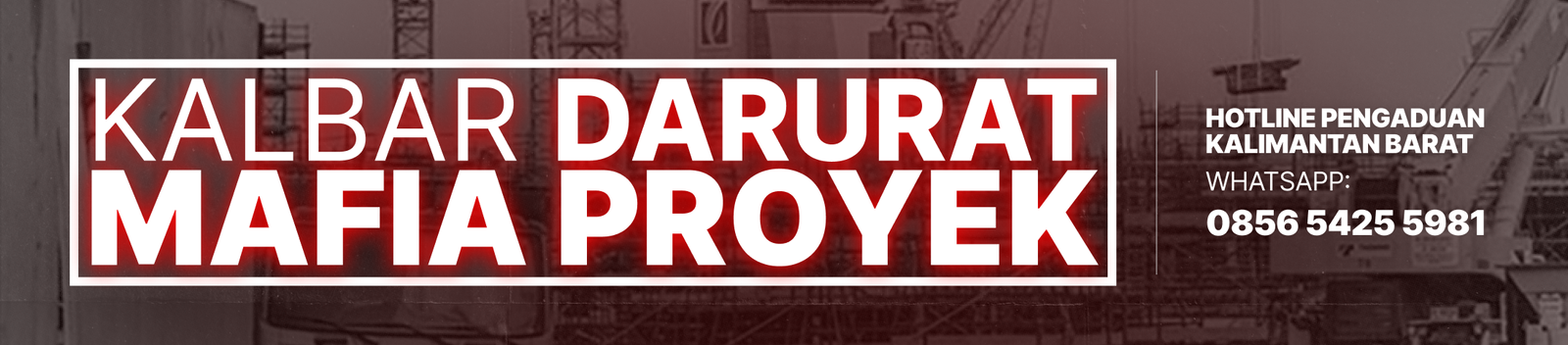Faktakalbar.id, LIFESTYLE – “Big Brother is Watching You.” Kalimat ikonik dari novel 1984 karya George Orwell ini ditulis pada tahun 1949, namun gaungnya terasa semakin nyaring di era digital saat ini.
Bagi banyak pembaca di Indonesia, menelusuri halaman-halaman kisah Winston Smith bukan lagi sekadar menikmati fiksi ilmiah, melainkan seperti menatap cermin yang memantulkan realita sosial dan politik bangsa.
Orwell melukiskan dunia distopia di mana kebenaran dimanipulasi, privasi dihapuskan, dan bahasa dikendalikan.
Lantas, seberapa dekat imajinasi mengerikan Orwell dengan kondisi Indonesia hari ini? Mari kita bedah satu per satu.
Baca Juga: Apa Itu Bibliophile? Cek Ciri-ciri Penggila Buku di Sini
1. Telescreen dan Panoptikon Digital (UU ITE)
Di Oceania (negara fiksi dalam novel), Telescreen adalah alat pengawas yang ada di setiap rumah, merekam gerak-gerik dan suara warga 24 jam. Tidak ada tempat untuk bersembunyi.
Di Indonesia, kita tidak memiliki Telescreen yang dipasang paksa di dinding, tetapi kita secara sukarela membawanya di saku: Smartphone.
Relevansi paling kuat terasa pada iklim ketakutan dalam berpendapat.
Keberadaan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), meski bertujuan mengatur ranah digital, sering kali memunculkan efek “Panoptikon” sebuah penjara di mana narapidana tidak tahu kapan mereka diawasi, sehingga mereka mendisiplinkan diri sendiri.
Banyak warganet Indonesia kini melakukan self-censorship (sensor mandiri) karena takut dikriminalisasi hanya karena kritik atau opini yang dianggap “mencemarkan nama baik”.
Pengawasan kini bukan hanya vertikal (negara ke rakyat), tapi juga horizontal (rakyat saling lapor), mirip dengan anak-anak di novel 1984 yang didoktrin untuk memata-matai orang tua mereka.
2. Newspeak dan Eufemisme Politik
Salah satu konsep paling brilian dari Orwell adalah Newspeak bahasa yang dirancang untuk membatasi jangkauan pemikiran.
Idenya sederhana: jika Anda tidak memiliki kata untuk sebuah konsep (misalnya “pemberontakan”), maka Anda tidak bisa memikirkannya.
Di Indonesia, kita akrab dengan permainan bahasa atau eufemisme politik yang bertujuan memperhalus realita pahit.
Perhatikan bagaimana istilah-istilah ini digunakan:
- Bukan “kenaikan harga”, melainkan “penyesuaian harga”.
- Bukan “penggusuran”, melainkan “relokasi” atau “penertiban”.
- Bukan “banjir”, melainkan “genangan”.
Penggunaan istilah-istilah ini, seperti halnya Newspeak, bertujuan untuk meredam gejolak emosi publik dan memanipulasi persepsi terhadap kinerja pemangku kebijakan.
Ketika bahasa dikendalikan, realitas objektif menjadi kabur.
3. Doublethink dan Polarisasi “Buzzer”
Doublethink adalah kemampuan untuk memercayai dua hal yang bertentangan secara bersamaan sebagai kebenaran, tergantung apa yang diperintahkan Partai.
Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat jelas di media sosial, terutama dengan keberadaan “pasukan siber” atau buzzer.
Loyalitas buta terhadap tokoh politik atau kelompok tertentu sering kali mematikan nalar kritis.
Masyarakat bisa membenci korupsi setengah mati, namun memaafkan (bahkan membela) korupsi jika pelakunya berasal dari kubu yang mereka dukung.
Fakta tidak lagi menjadi landasan kebenaran; “kebenaran” ditentukan oleh siapa yang berbicara.
Narasi sejarah dan fakta hari ini bisa diputarbalikkan (gaslighting) sedemikian rupa hingga masyarakat bingung membedakan mana berita asli dan mana fabrikasi.
4. Kementerian Kebenaran (Ministry of Truth)
Tugas Winston Smith di Ministry of Truth adalah menulis ulang artikel koran lama agar sesuai dengan kebijakan Partai hari ini.
“Siapa yang menguasai masa lalu, menguasai masa depan. Siapa yang menguasai masa kini, menguasai masa lalu.”
Di Indonesia, perdebatan mengenai sejarah tidak pernah usai.
Mulai dari kontroversi seputar peristiwa 1965, Supersemar, hingga peran tokoh-tokoh tertentu dalam sejarah kemerdekaan.
Upaya meluruskan sejarah sering kali bentrok dengan narasi penguasa yang ingin menjaga legitimasi.
Buku-buku “kiri” yang disita, diskusi yang dibubarkan, atau kurikulum yang berubah-ubah adalah bentuk nyata dari upaya mengontrol memori kolektif bangsa agar selaras dengan kepentingan kekuasaan saat ini.
5. Kaum Proletar dan Hiburan yang Melenakan
Dalam 1984, kaum Proletar (rakyat jelata) dibiarkan hidup relatif bebas, tetapi dibodohi dengan hiburan murahan, judi, dan pornografi agar mereka tidak sempat memikirkan pemberontakan.
“Selama mereka tidak sadar, mereka tidak akan memberontak.”
Lihatlah lanskap konten digital kita.
Algoritma media sosial membanjiri kita dengan joget viral, drama selebriti, dan konten sensasional yang menumpulkan daya kritis.