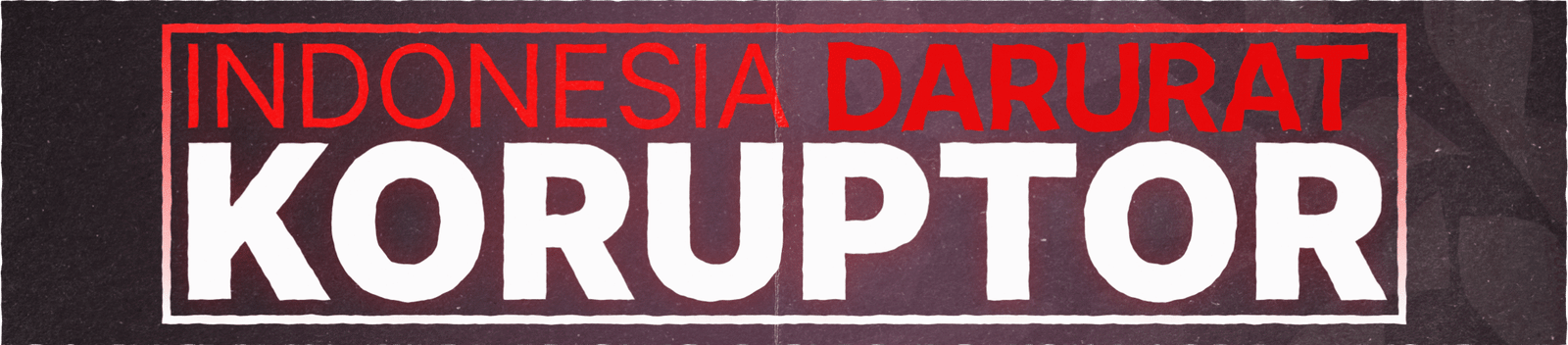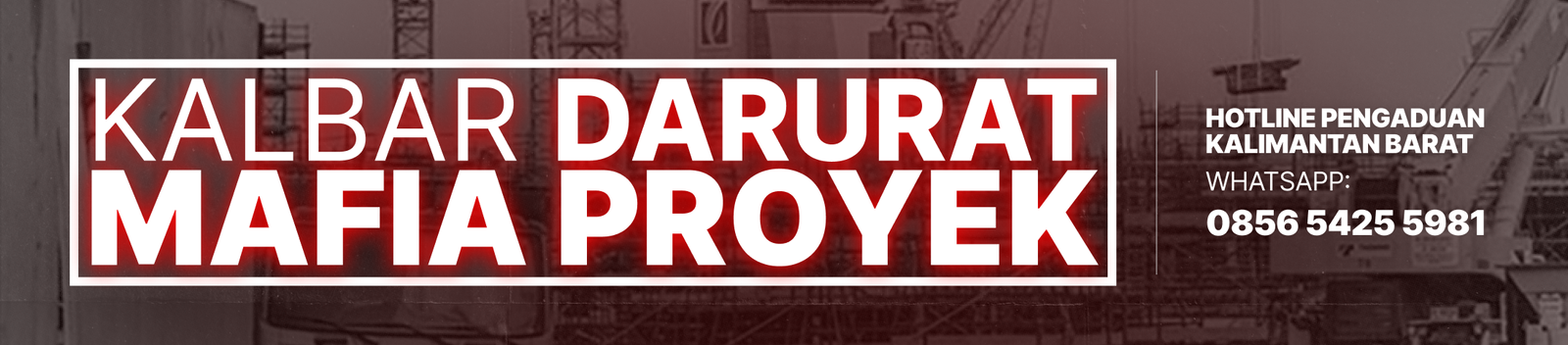Faktakalbar.id, LIFESTYLE – Masyarakat sering melihat jurnalis sebagai sosok yang tangguh, gigih mengejar narasumber, dan mampu berbicara lantang di depan kamera meski di tengah kekacauan.
Profesi ini dituntut untuk “objektif” dan “tahan banting”. Namun, di balik rompi pers dan kartu identitas itu, ada manusia biasa yang memiliki hati dan emosi.
Sering kali, berita yang sampai ke layar kaca atau gawai Anda telah melalui proses penyuntingan yang rapi.
Namun, memori visual dan emosional yang direkam oleh mata sang jurnalis tidak bisa disunting semudah itu.
Baca Juga: 5 Film Terbaik Tentang Jurnalis yang Mengungkap Kekuatan ‘Pilar Keempat’
Banyak pewarta mengalami apa yang disebut Vicarious Trauma (trauma sekunder) akibat paparan terus-menerus terhadap tragedi.
Berikut adalah 5 hal utama yang kerap membuat mental jurnalis terguncang saat bertugas.
1. Paparan Visual yang Mengerikan (Tanpa Sensor)
Saat terjadi kecelakaan maut, pembunuhan sadis, atau bencana alam, publik melihat foto yang sudah disensor atau diburamkan (blur).
Namun, jurnalis di lapangan melihatnya secara “mentah”.
Melihat jenazah yang tidak utuh, mencium aroma amis darah di TKP, atau mendengar jeritan kesakitan para korban secara langsung adalah pengalaman sensorik yang bisa menghantui tidur selama berminggu-minggu.
Otak manusia tidak didesain untuk menyaksikan kematian dan kehancuran secara rutin, dan akumulasi memori visual ini bisa memicu PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder).
2. “Dosa” Mewawancarai Keluarga Korban
Ini adalah dilema batin terbesar bagi banyak jurnalis.
Di satu sisi, editor menuntut konfirmasi atau kutipan emosional agar berita memiliki nilai berita (news value).
Di sisi lain, hati nurani berteriak bahwa tidak etis menyorongkan mikrofon ke wajah seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya.
Momen ketika harus “memaksa” masuk ke ruang privasi orang yang sedang berduka sering kali meninggalkan rasa bersalah (moral injury) yang mendalam.
Jurnalis merasa seperti “burung pemakan bangkai” yang mengeksploitasi kesedihan orang lain demi sebuah berita.
3. Teror dan Intimidasi Pihak Berkuasa
Meliput kasus korupsi, sengketa lahan, atau kejahatan terorganisir memiliki risiko tinggi. Ancaman tidak selalu berupa kekerasan fisik, tapi juga teror psikologis.
Panggilan telepon misterius di tengah malam, mobil yang dibuntuti orang tak dikenal, hingga ancaman terhadap keselamatan keluarga di rumah adalah hal yang nyata.
Hidup dalam mode “waspada tinggi” (hypervigilance) terus-menerus membuat sistem saraf jurnalis kelelahan, memicu kecemasan kronis dan paranoia.
4. Serangan Digital (Doxing & Cyberbullying)
Di era digital, ancaman berpindah ke media sosial.
Saat jurnalis memberitakan kasus kontroversial yang menyinggung kelompok fanatik tertentu, mereka rentan menjadi target doxing (penyebaran data pribadi).
Ribuan komentar kebencian, cacian fisik (body shaming), hingga ancaman pembunuhan yang masuk ke DM (Direct Message) pribadi bisa meruntuhkan mental sekuat apa pun.
Perasaan tidak aman ini bahkan terasa saat mereka sedang bersantai di rumah, karena teror ada di dalam genggaman tangan (ponsel) mereka.
5. Rasa Tidak Berdaya (Helplessness)
Jurnalis sering kali meliput kemiskinan ekstrem atau ketidakadilan hukum.
Mereka melihat penderitaan di depan mata, namun terikat kode etik bahwa tugas mereka hanya “melaporkan”, bukan “mencampuri”.
Ada rasa frustrasi yang luar biasa ketika berita yang mereka tulis dengan susah payah ternyata tidak mengubah keadaan.
Koruptor tetap bebas, korban tetap miskin, dan keadilan tetap tumpul. Perasaan “percuma” ini bisa memicu burnout dan depresi karena merasa pekerjaan mereka tidak memiliki dampak nyata.
Kesimpulan: Jurnalis Perlu Ruang untuk Pulih
Tulisan ini bukan untuk menakut-nakuti calon jurnalis, melainkan untuk membangun kesadaran (awareness).
Bahwa di balik setiap berita yang kita baca, ada pengorbanan mental dari penulisnya.
Sudah saatnya industri media dan masyarakat menormalisasi bahwa jurnalis juga boleh merasa sedih, boleh menangis, dan berhak mendapatkan dukungan psikologis.
Mereka adalah pembawa pesan, bukan robot tanpa perasaan.
Baca Juga: Jurnalis Jadi Korban Kekerasan, Media Diintervensi dan Dibungkam Warnai Aksi 25–30 Agustus 2025
(*Mira)