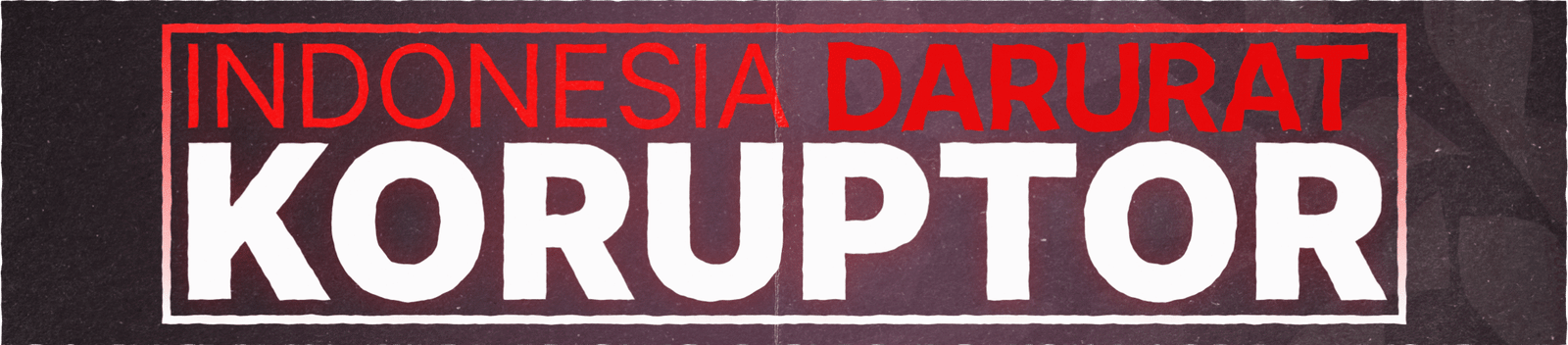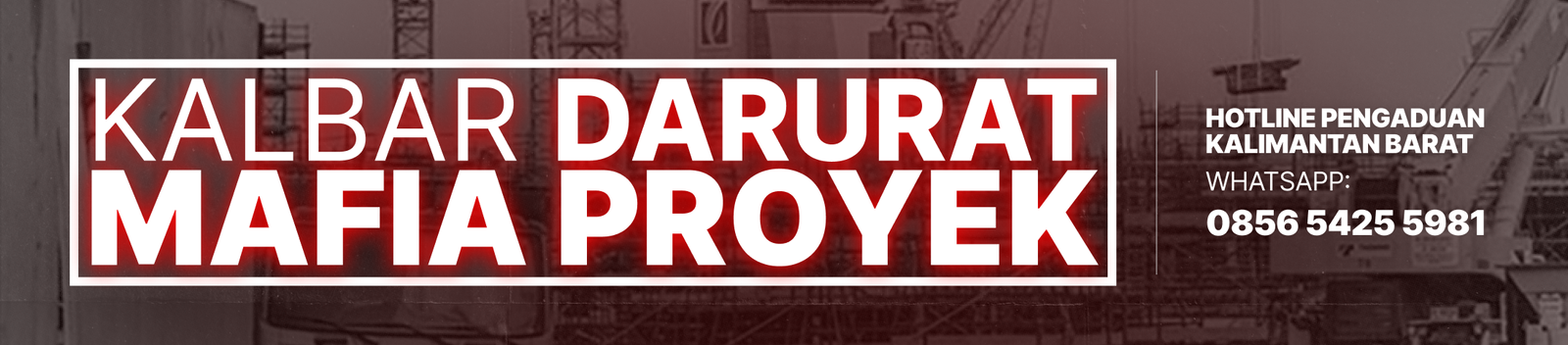OPINI – Wacana mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD bukan sekadar perdebatan teknis ketatanegaraan.
Ia adalah pertaruhan ideologis tentang siapa yang berhak menentukan arah kekuasaan di republik ini. Apakah rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan, atau elite politik yang mengatasnamakan representasi?
Baca Juga: Wacana Pilkada via DPRD Menguat, KPK Ingatkan Risiko Korupsi Akibat Biaya Politik Mahal
Dalam sejarah demokrasi modern Indonesia, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu koreksi paling signifikan terhadap praktik politik elitis era Orde Baru.
Ia lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan yang hanya berputar di lingkaran elite cenderung melahirkan penyalahgunaan wewenang, korupsi struktural, dan keterputusan antara negara dan warga. Karena itu, setiap upaya untuk menarik kembali hak politik rakyat harus dibaca sebagai langkah regresif, bukan inovatif.
Dari Vox Populi ke Vox Elite
Pemilihan langsung kepala daerah adalah perwujudan paling konkret dari adagium vox populi vox dei. Rakyat tidak hanya diminta patuh pada keputusan elite, tetapi diberi hak menentukan siapa yang memerintah mereka.
Ketika mekanisme ini hendak digantikan oleh pemilihan melalui DPRD, yang terjadi bukan sekadar perubahan metode, melainkan pergeseran pusat kedaulatan.
Kedaulatan yang semula berada di tangan jutaan pemilih dialihkan ke tangan segelintir anggota legislatif. Dari ruang publik yang terbuka, demokrasi dipindahkan ke ruang negosiasi politik yang tertutup.
Baca Juga: KPK Soroti Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tekankan Pentingnya Tutup Celah Korupsi
Ini bukan sekadar penyederhanaan prosedur, tapi sebuah tindakan sadar penyempitan makna demokrasi sekaligus pengebirian demokrasi itu sendiri.
Dalih bahwa DPRD adalah representasi rakyat sering dikemukakan. Namun representasi tidak identik dengan substitusi total. Dalam teori demokrasi, representasi justru harus memperkuat partisipasi rakyat, bukan menggantikannya. Ketika hak memilih pemimpin eksekutif dicabut dari rakyat, representasi berubah menjadi legitimasi semu bagi dominasi elite.
Ilusi Efisiensi dan Fakta Politik Transaksional
Alasan yang paling sering digunakan untuk membenarkan perubahan ini adalah efisiensi biaya dan stabilitas politik. Argumen ini terdengar rasional di permukaan, tetapi rapuh secara empiris. Sejumlah pengamat justru melihatnya sebagai ilusi efisiensi yang menutup mata terhadap realitas politik transaksional.
faktanya, bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak akan menghilangkan politik uang. Ia hanya mengubah bentuk dan lokasinya. Jika sebelumnya transaksi terjadi di ruang publik dengan segala risikonya, kini ia berpindah ke ruang elite yang lebih steril dari pengawasan publik.
Pandangan ini menegaskan bahwa pemilihan langsung merupakan implementasi nyata prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Menghapusnya berarti mengurangi hak politik warga negara dan membuka ruang lebih luas bagi transaksi kekuasaan yang sulit dikontrol.
Alih-alih menurunkan biaya politik, sistem ini justru berpotensi memadatkan biaya pada aktor-aktor kunci DPRD. Harga politik tidak menjadi murah, tetapi menjadi eksklusif.
Oligarki Lokal dan Konsolidasi Kekuasaan Partai
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak bisa dilepaskan dari kecenderungan menguatnya oligarki politik di tingkat lokal. Ketika kepala daerah ditentukan oleh elite partai dan fraksi legislatif, maka loyalitas politik kepala daerah akan lebih condong ke partai ketimbang ke rakyat.
Dalam situasi ini, kepala daerah berpotensi berubah dari pelayan publik menjadi manajer kepentingan politik. Kebijakan publik pun rawan disandera oleh kompromi elite, bukan
kebutuhan warga, sehingga wacana ini dapat dibaca sebagai kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998. Dimana reformasi lahir untuk meruntuhkan dominasi elite dan membuka ruang partisipasi rakyat.
Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD justru berpotensi mereproduksi logika kekuasaan lama dengan wajah baru. Dalam perspektif politik progresif, ini adalah bentuk retrenchment demokrasi—penarikan kembali hak-hak politik rakyat atas nama stabilitas dan efisiensi.
Efek Domino: DPRD sebagai Komoditas Kekuasaan
Dampak paling berbahaya dari perubahan ini justru terletak pada implikasinya terhadap pemilu legislatif. Ketika DPRD menjadi penentu kepala daerah, maka kursi legislatif berubah menjadi komoditas kekuasaan bernilai tinggi.