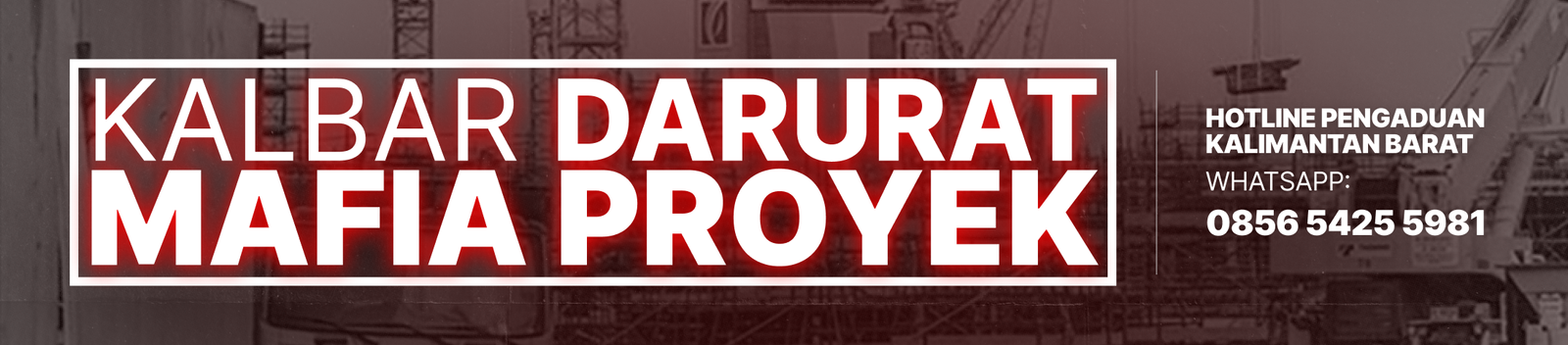OPINI – Dua tragedi dalam sepekan terakhir mengguncang nurani warga Kota Pontianak. Dua pria muda, VP (24 tahun) dan JI (36 tahun), ditemukan meninggal dunia karena dugaan bunuh diri.
Kematian yang datang diam-diam, tanpa pamit, tanpa pesan. Hanya keheningan yang tersisa, meninggalkan duka mendalam dan pertanyaan yang menggantung, “Apa yang sebenarnya terjadi?”
Sebagian mungkin memilih menganggapnya sebagai urusan pribadi, ranah domestik yang tak layak dicampuri. Namun, kita tak bisa terus bersembunyi di balik dalih itu.
Tragedi ini bukan semata tentang individu yang merasa kalah, melainkan cermin retak dari kondisi sosial kita hari ini sistem yang gagal menyediakan ruang aman bagi mereka yang ingin bersuara tentang luka batin mereka.
Baca Juga: Membangun Desa Cendekia: Jalan Emas Menuju Kesejahteraan dan Keadilan Ekologis
Kita sedang menghadapi krisis yang kerap luput dari perhatian, yaitu krisis kesehatan mental pada laki-laki. Krisis ini hadir dalam senyap, tak terlihat, namun nyata dan mematikan.
Jika masyarakat, negara, dan institusi keagamaan tidak segera bertindak, maka kesunyian ini akan terus merenggut nyawa mereka yang terabaikan.
Sejak kecil, laki-laki dibentuk dalam kerangka “kuat”, “tangguh”, dan “tegar”. Mereka diajari menahan tangis, menekan emosi, dan menyembunyikan rasa takut. Semua ekspresi manusiawi dijinakkan atas nama maskulinitas.
Maka ketika terluka, mereka diam. Ketika hancur, mereka menyendiri. Bukan karena tak merasa, tetapi karena tak tahu bagaimana menyampaikannya, atau merasa tidak akan dipercaya, tidak diterima, bahkan mungkin dihina.
Dalam budaya semacam ini, banyak laki-laki dewasa tumbuh dalam kehidupan sosial yang dangkal secara emosional.
Persahabatan dibangun di atas aktivitas, bukan kedekatan batin. Di rumah, mereka dituntut menjadi penopang ekonomi, bukan penerima dukungan emosional.
Di tempat kerja, mereka harus terus tampil prima tanpa ruang untuk gagal. Ketika hidup mulai runtuh, tak ada tempat bersandar.
Tekanan ekonomi, ekspektasi budaya, relasi sosial yang rapuh, serta keterasingan spiritual menjadi bom waktu. Ketika semuanya meledak bersamaan, mereka menyimpan segalanya sendiri, berharap waktu menyembuhkan. Padahal waktu tidak menyembuhkan, ia hanya menumpuk luka.
Data WHO menunjukkan, laki-laki Indonesia 3,5 kali lebih berisiko meninggal akibat bunuh diri dibanding perempuan.
Secara global, World Journal of Psychiatry (2022) mencatat bahwa 7 dari 10 kasus bunuh diri dilakukan oleh laki-laki.
Baca Juga: KBIHU DIHINA, UMAT BICARA
Ini bukan sekadar angka. Ini jeritan yang tak terdengar, permintaan tolong yang tak pernah kita dengarkan.
Ironisnya, perempuan lebih sering terdiagnosis gangguan mental, namun laki-laki lebih sering meninggal karenanya.
Perempuan cenderung lebih terbuka dan mencari bantuan. Laki-laki, sebaliknya, lebih pandai menyembunyikan luka hingga tak lagi mampu.
Islam sendiri tidak menolak ekspresi kesedihan. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam menangis saat putranya wafat dan bersedih berbulan-bulan setelah Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia.
Al-Qur’an mencatat bagaimana Nabi Ya’qub menangis hingga matanya memutih karena kehilangan Yusuf (QS. Yusuf: 84). Kesedihan bukanlah aib.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id