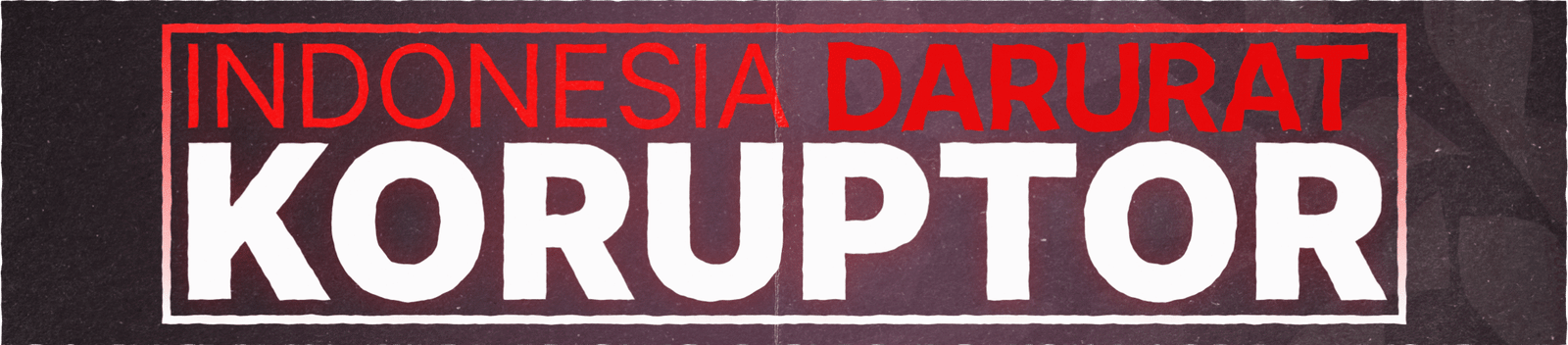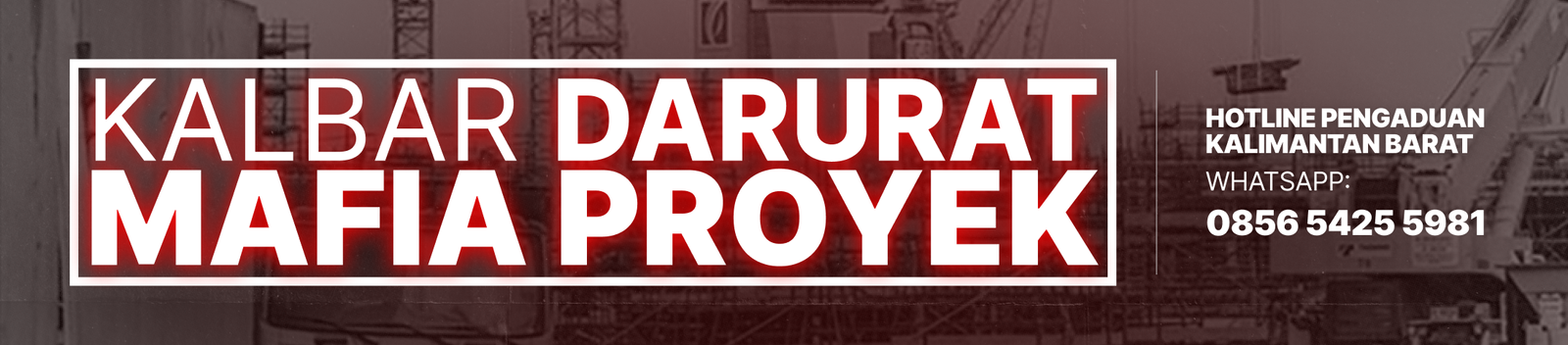OPINI – Tulisan ke 8 edisi Ramadan. Tragedi paling berdarah dalam Islam dimulai dari Khalifah Utsman bin Affan. Rumahnya dikepung sampai 40 hari, lalu diterobos, nyawanya dihabisi dengan sangat kejam. Simak kisahnya sambil seruput koptagul usai buka puasa, wak!
Mekkah abad ke 6 seperti pusat konglomerasi tanpa etika audit, tempat para saudagar berlomba menumpuk dirham dan gengsi. Di tengah panggung itu berdiri seorang pria yang hartanya bisa membuat bangsawan Persia dan Bizantium melirik iri.
Dialah Utsman bin Affan. Lahir sekitar 573 sampai 576 M dari Bani Umayyah, yatim sejak kecil karena ayahnya, Affan, wafat lebih dulu, ia tumbuh sebagai salah satu orang terkaya di Jazirah Arab. Tapi kekayaan itu tak membuatnya liar.
Ia tak menyentuh khamar, tak gemar berteriak, dan dikenal pemalu luar biasa. Bisa baca tulis di tengah masyarakat yang mayoritas buta huruf. Dermawan tanpa panggung. Sopan sampai malaikat pun disebut malu kepadanya.
Tahun keenam kenabian, ia diajak sahabatnya, Abu Bakr ash Shiddiq, memeluk Islam. Tanpa drama. Tanpa negosiasi politik. Keluarga menekan, paman mengancam, tapi ia tetap tegak.
Ia menikahi Ruqayyah, putri Muhammad, lalu hijrah pertama ke Habasyah pada 615 M, gelombang hijrah paling awal dalam sejarah Islam. Kemudian, hijrah kedua ke Madinah. Setelah Ruqayyah wafat, ia menikahi Ummu Kultsum.
Dua putri Nabi dinikahinya, hingga Rasulullah menjulukinya Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Ia tak ikut Perang Badar karena merawat istrinya yang sakit, namun tetap diberi bagian ghanimah dan pahala penuh. Seolah langit sendiri tahu, pengabdian tak selalu bersuara pedang.
Tahun 644 M, setelah Umar bin Khattab wafat akibat tikaman, enam tokoh besar (Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa’d bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah) bermusyawarah.
Utsman terpilih dalam usia 68 sampai 71 tahun, menjadi khalifah tertua di antara Khulafaur Rasyidin. Ia berjanji berpegang pada Alquran dan sunnah Abu Bakr Umar. Masa pemerintahannya 12 tahun menyaksikan ekspansi besar dari Armenia, Khurasan, Afrika Utara.
Armada laut Muslim pertama bahkan mengalahkan Bizantium dalam Pertempuran Layar Besar tahun 655 M. Namun kebijakan paling monumental adalah standardisasi Alquran.
Karena perbedaan bacaan di berbagai provinsi, ia memerintahkan Zaid bin Tsabit menyusun mushaf resmi, menyalinnya dan mengirimkannya ke berbagai wilayah, serta membakar mushaf lain demi persatuan.
Tujuannya menyatukan umat. Tapi seperti biasa, kebijakan persatuan sering dipelintir jadi bahan tuduhan.
Ia membeli sumur Rumah di Madinah dengan puluhan ribu dirham dari hartanya sendiri dan mewakafkannya gratis selamanya. Ia memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, membebaskan budak setiap Jumat, mengirim bantuan pangan saat paceklik.
Seorang khalifah super kaya yang hidup sederhana. Namun ketika ia mengangkat beberapa kerabat sebagai gubernur, tuduhan nepotisme meledak. Politik memang tak pernah kekurangan cara untuk mengubah amal menjadi kecurigaan.
Lalu tibalah bab paling gelap, 40 hari pengepungan. Tahun 656 M, sekitar 500 hingga 1.000 orang dari Mesir, Kufah, dan Basrah datang ke Madinah.
Rumah khalifah dikepung selama 40 sampai 49 hari. Air diputus. Makanan ditahan. Tuduhan dilontarkan. Nepotisme, korupsi, menyimpang dari sunnah.
Sebuah surat misterius, diduga terkait Marwan bin al Hakam yang memerintahkan pembunuhan pemimpin delegasi Mesir dicegat, memicu ledakan amarah. Isu berembus tentang figur seperti Abdullah bin Saba’. Propaganda menyebar cepat. Fitnah berubah jadi keyakinan.
Para sahabat siap membela. Ali mengirim Hasan dan Husain berjaga. Para pemuda Anshar menghunus pedang.
Satu perintah dari Utsman saja, Madinah bisa berubah jadi medan perang. Tapi ia menolak. “Aku tidak ingin menjadi orang pertama yang menumpahkan darah umat setelah Rasulullah.” Ia memilih bersabar. Pilihan yang terdengar lembut, tapi sesungguhnya seberat gunung.
Jumat, 18 Dzulhijjah 35 H. Ia berpuasa. Duduk membaca mushaf di rumahnya bersama istrinya, Nailah. Karena rasa malunya, ia tetap mengenakan seluar agar aurat tak terbuka bahkan saat dibunuh.
Rumahnya diterobos. Muhammad bin Abu Bakr sempat mencengkeram jenggotnya, namun mundur setelah diingatkan dengan lembut tentang ayahnya. Tapi yang lain tak berhenti.
Kinanah bin Bisyr memukul kepalanya dari belakang. Sudan bin Humran menebas lagi. Amr bin al Hamiq duduk di dadanya dan menusuk perutnya enam hingga sembilan kali.
Nailah melindungi suaminya, jari jarinya terpotong oleh tebasan. Darah mengalir. Menetes ke mushaf yang sedang dibaca, pada ayat ayat tentang kesabaran.
Di situlah judul ini menemukan maknanya, satu mushaf berdarah.
Ia wafat dalam keadaan puasa, usia 82 tahun. Syahid. Jenazahnya tertahan tiga hari sebelum dimakamkan diam diam di Jannatul Baqi’. Tanpa upacara besar. Tanpa pengawalan megah. Hanya sunyi dan pilu.
Seorang khalifah yang membeli sumur untuk umat, memperluas masjid dengan hartanya sendiri, menyatukan mushaf agar tak ada perpecahan bacaan, akhirnya gugur oleh fitnah yang mengatasnamakan perbaikan.
Baca Juga: Abu Lahab & Abu Jahal, Duo Oposisi Abadi yang Takut Kehilangan Kursi
Ia bisa saja mempertahankan kekuasaan dengan pedang. Tapi ia memilih mempertahankan persatuan dengan nyawanya.
Empat puluh hari pengepungan itu bukan sekadar episode sejarah. Itu retakan pertama dalam tubuh umat yang dampaknya terasa berabad abad. Setiap kali mushaf Utsmani dibaca hari ini, ada jejak darah seorang lelaki tua yang memilih kesabaran daripada perang saudara.
Empat puluh hari dikepung. Satu mushaf berdarah. Sebuah kesabaran yang tak pernah benar benar mati.
Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar