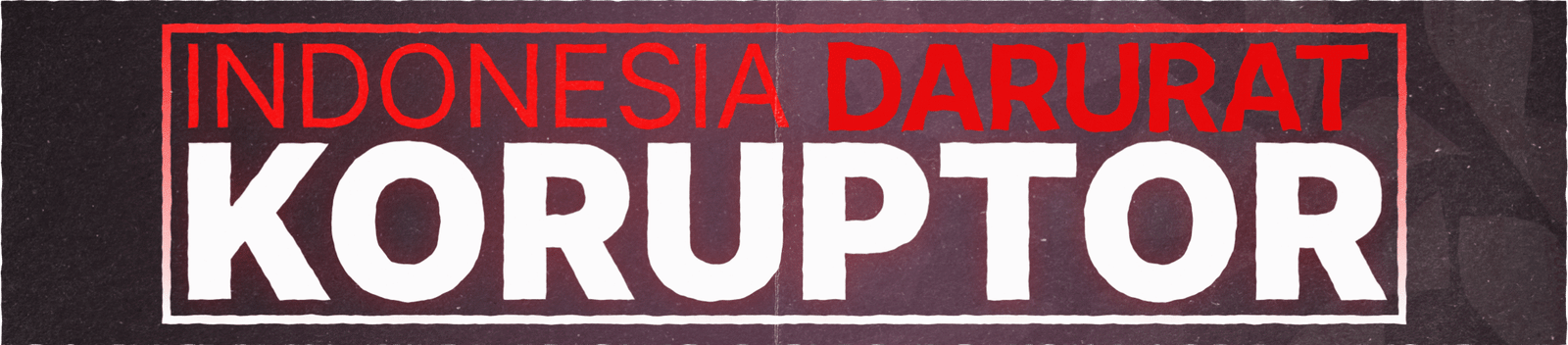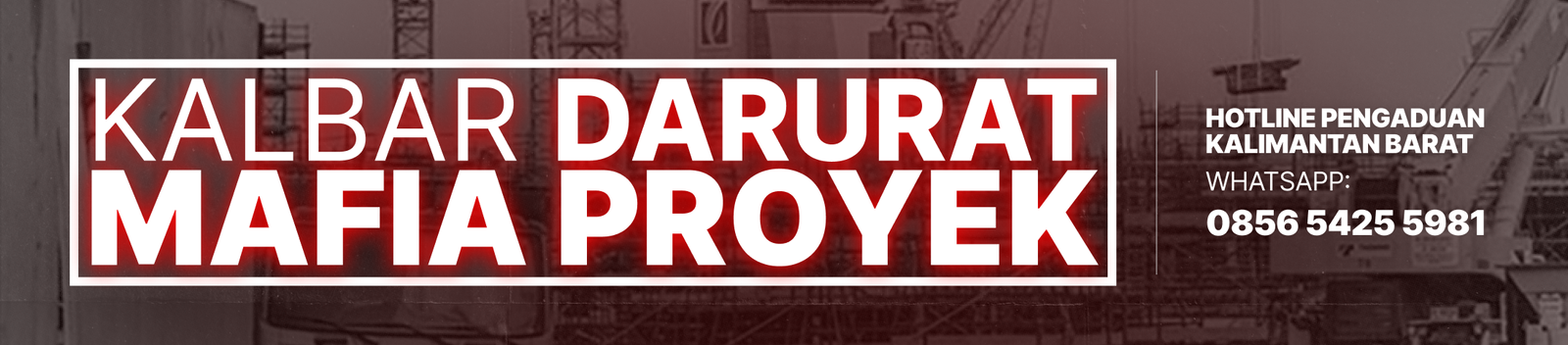Tidak ada paspor cadangan. Tidak ada jalan pintas. Yang ada hanya latihan panjang, kaki lecet, dan keyakinan bodoh bahwa mimpi besar bisa dikejar dengan cara jujur.
Saat penalti terakhir gagal, Indonesia Arena tidak meledak, ia retak. Enam belas ribu penonton terdiam bersamaan, seperti baru saja kehilangan sesuatu yang tak bisa diulang. Di media sosial, tangis berubah menjadi kalimat pendek.
Karena, air mata terlalu banyak untuk dirangkai. Ada anak kecil yang besoknya minta latihan lagi. Seolah ingin membalas rasa kecewa dengan kerja keras. Ada orang dewasa yang menangis diam-diam, karena untuk pertama kalinya ia benar-benar berharap.
Héctor Souto berdiri mematung. Ia tahu, dalam adu penalti, kecerdasan tak lagi berkuasa. Ia sudah membawa Indonesia sejauh mungkin, ke depan singgasana raja Asia. Tinggal satu langkah. Satu tendangan. Tapi takdir memilih kejam, karena sejarah sering meminta pengorbanan sebelum memberi mahkota.
Malam itu, Indonesia kalah.
Tapi tidak hina.
Tidak kecil.
Tidak bodoh.
Indonesia kalah dalam posisi berdiri tegak, tepat di depan tahta.
Justru di situlah air mata ini menjadi penting. Karena bangsa yang bisa menangis atas perjuangan jujur, adalah bangsa yang suatu hari akan menang, tanpa perlu berteriak lagi.
Garuda pulang dengan sayap basah. Namun luka itu…adalah tanda bahwa ia sudah belajar terbang terlalu tinggi untuk kembali merangkak.
Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.