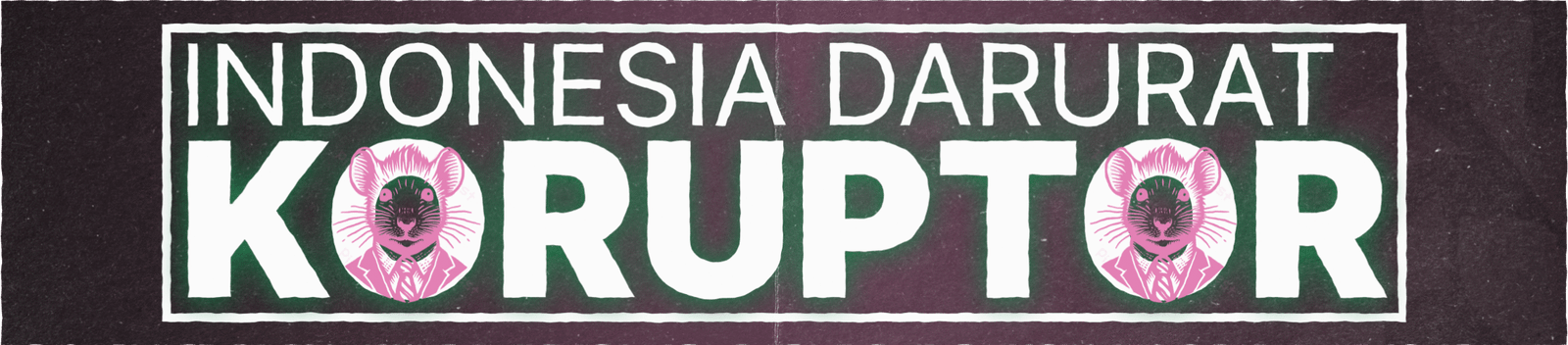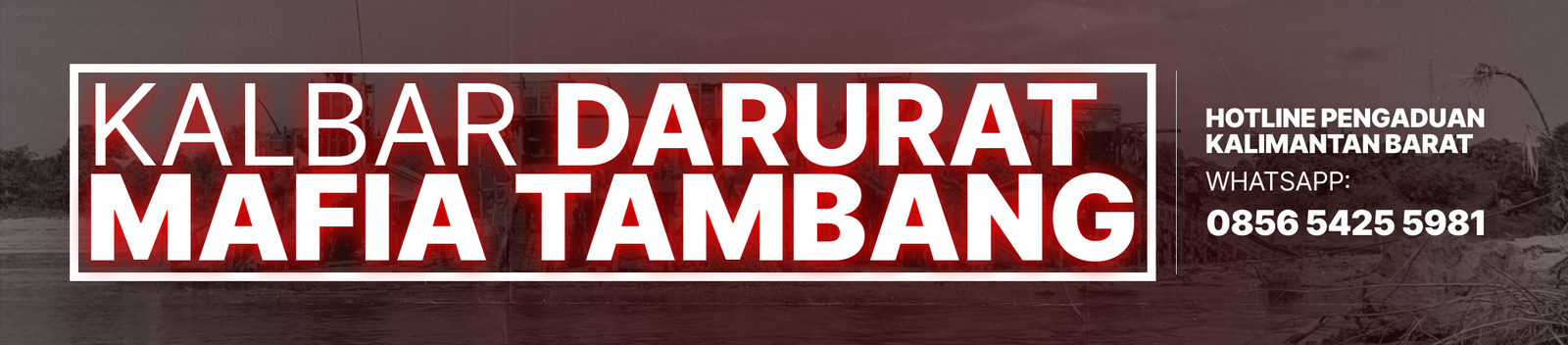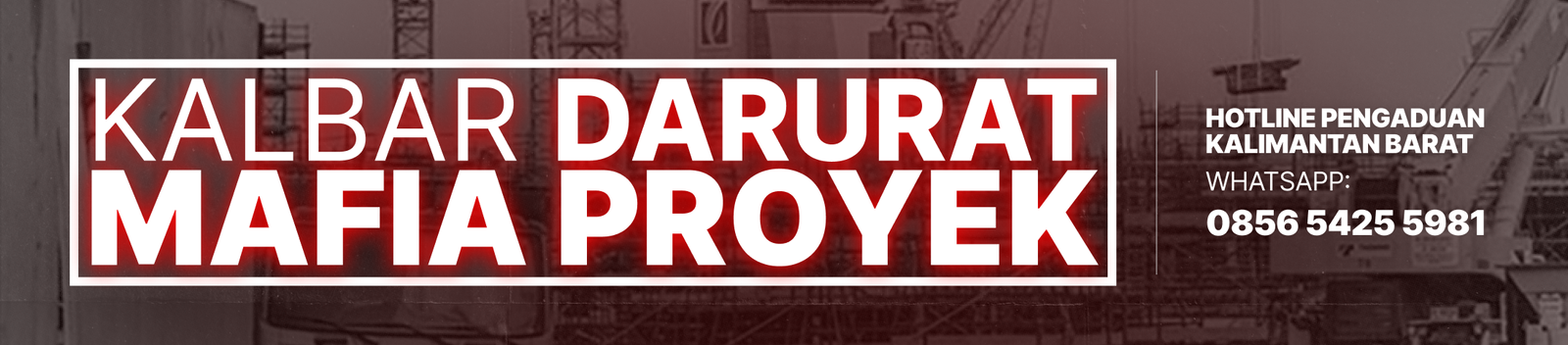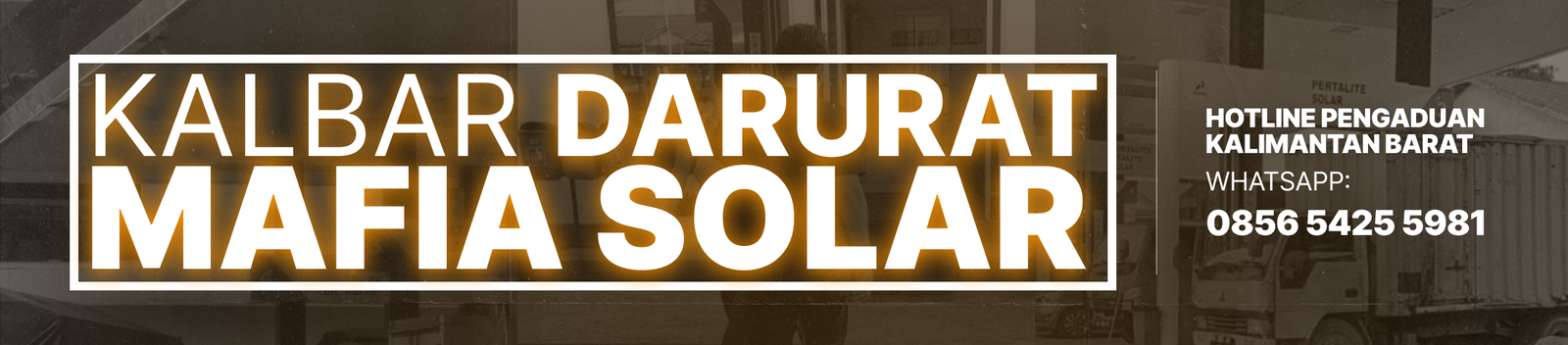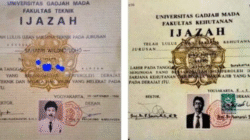Di tengah tantangan global perubahan iklim, narasi pembangunan di wilayah-wilayah terluar Indonesia tidak lagi cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.
Ia harus berpijak pada keadilan ekologis dan partisipasi sosial. Kalimantan Barat, dengan seluruh kekayaan hayati dan tantangan sosialnya, menjadi potret sempurna tentang dilema dan harapan itu.
Salah satu isu paling pelik yang terus membayangi adalah keberadaan tambang emas tanpa izin (PETI) yang merusak ribuan hektar lahan subur, mencemari air, dan menciptakan kerusakan sosial yang sulit diukur.
Namun, di balik setiap luka ekologis, tersimpan peluang pemulihan dan pembaruan tata kelola. Di Desa Kedabang, Kabupaten Sintang, sebuah model restorasi ekologis sedang dibangun untuk menjawab tantangan ini.
Model ini tidak hanya menyembuhkan luka alam, tetapi juga mencoba mengubah logika pendekatan terhadap PETI dari pendekatan represif menjadi transformatif, dari ilegal menjadi legal dan berkelanjutan.
Krisis Lingkungan dan Sosial dari PETI
Kegiatan PETI bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga cermin dari kegagalan negara menyediakan ruang legal yang inklusif bagi warga yang menggantungkan hidupnya pada emas.
Tanpa izin, tanpa teknologi ramah lingkungan, dan tanpa mitigasi, aktivitas PETI telah meninggalkan jejak degradasi serius. Lapisan tanah atas terangkat, air terkontaminasi merkuri, dan vegetasi alami tergantikan oleh danau-danau buatan yang menganga.
Penelitian di Kedabang menunjukkan bahwa setelah 25 hingga 40 tahun pasca-aktivitas PETI, regenerasi alami berjalan sangat lambat.
Dominasi vegetasi pionir seperti resam dan paku kawat menunjukkan bahwa tanah tak lagi subur untuk menunjang pertumbuhan vegetasi sekunder.
Keasaman tanah tinggi, kandungan hara rendah, dan kepadatan tanah yang ekstrem menjadi kendala utama pemulihan alami.
Model Restorasi yang Konkrit dan Terukur
Untuk menjawab situasi ini, kami mengembangkan model restorasi lahan bekas tambang berbasis empat pilar:
- Pemulihan kesuburan tanah melalui penggunaan pupuk kandang dan kompos blok bersertifikat SNI;
- Penggunaan hidrogel/Alcosorb untuk mempertahankan kelembaban;
- Pemanfaatan tanaman penutup tanah jenis Pueraria javanicum sebagai pionir.
- Media tanam berbasis campuran tanah liat dan bahan organik.
Model ini dirancang dengan pendekatan partisipatif masyarakat. Komunitas dilibatkan dalam produksi kompos, pembibitan, penanaman, dan monitoring pertumbuhan.
Selain menekan biaya, ini membangun rasa memiliki dan memastikan keberlanjutan pasca-proyek.
FOLU Net Sink 2030 dan Insentif atas Restorasi
Lebih dari sekadar memulihkan tutupan lahan, restorasi ini ditautkan dengan target nasional FOLU Net Sink 2030.
Dengan meningkatkan cadangan karbon dari vegetasi dan tanah, kegiatan ini menyumbang pada pilar peningkatan karbon (Enhancement of Carbon Stock).
Oleh karena itu, kami mendorong agar mekanisme insentif berbasis hasil (result-based payment) diberikan kepada komunitas yang sukses meningkatkan stok karbon terverifikasi, baik melalui SRN, GCF, maupun program REDD+ subnasional.
Dengan dukungan satelit, drone, dan sistem MRV, pencapaian ini dapat diukur dan diverifikasi. Ketika karbon menjadi nilai ekonomi, maka restorasi bukan lagi beban, melainkan investasi masa depan.
Transformasi Kebijakan: Dari PETI ke IPR
Langkah strategis lainnya adalah transformasi pendekatan terhadap PETI. Pemprov Kalbar berinisiatif mendorong legalisasi tambang rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id