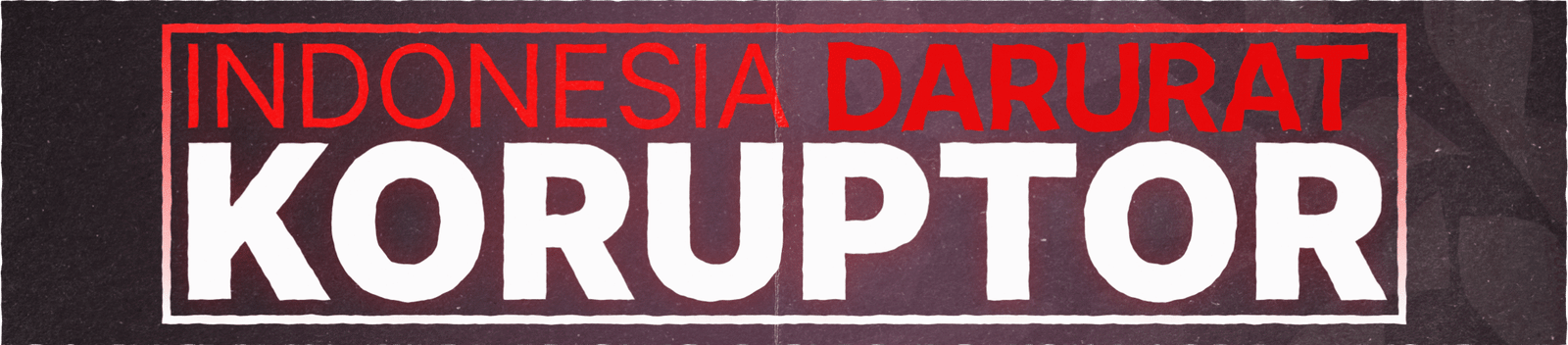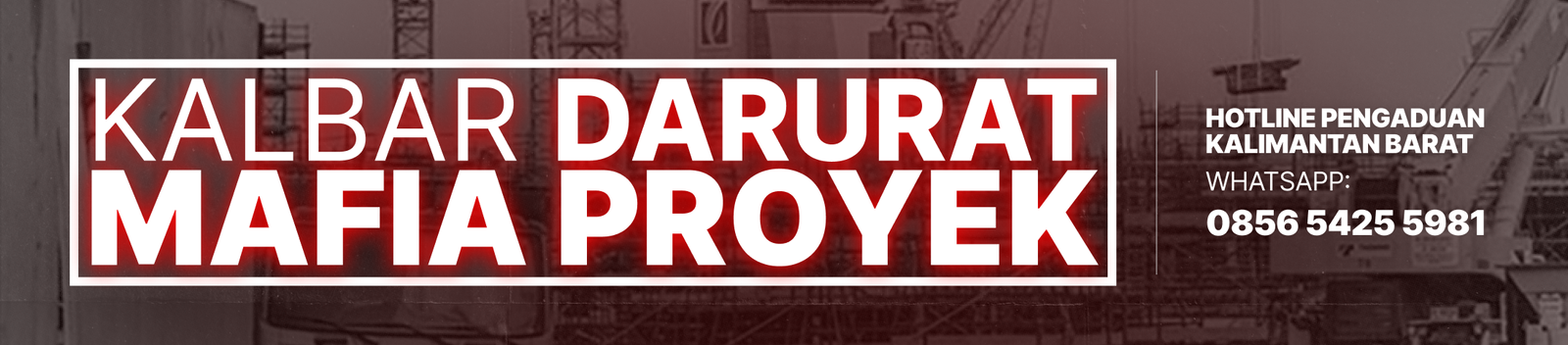Pada masa itu, peran perempuan dikonstruksi ulang (ibuisme negara) agar fokus utamanya hanya sebagai “pendamping suami” dan pengurus rumah tangga.
Ini memperkuat stigma bahwa wilayah kekuasaan perempuan hanyalah domestik: sumur (mencuci), dapur (memasak), dan kasur (melayani suami), mematikan potensi mereka di ranah publik.
4. Eufemisme yang Menipu
Sering kali kita mendengar alasan, “Pakai kata wanita saja, lebih halus.” Padahal, penghalusan makna (eufemisme) ini sering kali justru menyembunyikan realitas pahit.
Contohnya, istilah “Wanita Tuna Susila” digunakan untuk mengganti “Pelacur”.
Penggunaan kata “wanita” di sini seolah memberikan kesopanan semu, padahal tujuannya adalah melabeli moralitas.
Kata “Perempuan” dianggap lebih lugas, netral, dan setara secara manusiawi.
5. Simbol Ketidaksetaraan Posisi
Coba perhatikan pasangannya: “Pria dan Wanita”.
Pria berasal dari kata Vira (pahlawan/berani), sedangkan Wanita (yang diinginkan). Dari sini saja sudah terlihat ketimpangan derajat.
Sementara jika kita menggunakan “Laki-laki dan Perempuan”, keduanya memiliki kedudukan yang setara sebagai manusia, tanpa embel-embel sifat kepahlawanan di satu sisi dan sifat pasif di sisi lain.
Bahasa adalah cermin budaya.
Mengganti kata “Wanita” menjadi “Perempuan” bukan sekadar gonta-ganti istilah, melainkan upaya merebut kembali martabat dan otonomi.
Perempuan adalah Empu bagi dirinya sendiri, bukan sekadar sosok yang Wani Ditoto.
(*Mira)